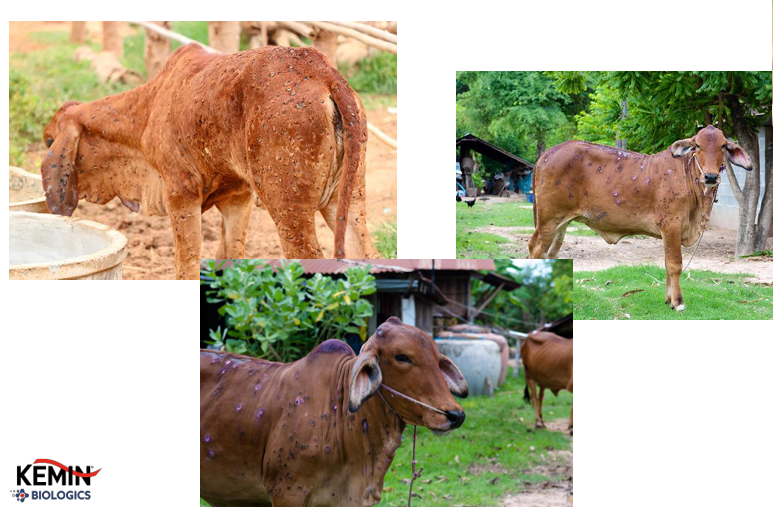Kemudahan budidaya tak menjamin pelaku usaha lele sukses mendulang untung. Pasar yang seluruhnya lokal dan hanya dalam bentuk segar, mempersempit gerak pembudidaya.
Jargon bahwa lele adalah ikan yang mudah dibudidayakan memang tak sepenuhnya salah. Ikan asal Afrika ini memang bisa hidup dalam air yang terbatas, cepat tumbuh, dan bisa makan segala jenis pakan. Namun, lain lagi jika pelaku berniat terjun ke usaha yang serius, bukan sekadar hobi. Memelihara ikan yang mudah ini jadi sulit karena harganya yang relatif murah dan produksinya melimpah. Tak heran kalau harganya tak pernah mencuat.
Biaya produksi satu kilo lele saat ini sekitar Rp8.500–Rp9.000. Harga jualnya berkisar Rp9.000–Rp11.000 di tingkat petani, sedangkan di tingkat konsumen mencapai Rp14.000 per kg. Di sisi lain, hampir seluruh produksi lele dipasarkan dalam bentuk segar yang volumenya cenderung stagnan. Jakarta misalnya, daya serapnya sekitar 85 ton per hari, Yogyakarta 20 ton per hari, dan Bogor 15 ton per hari. Pasar ini diperebutkan oleh produsen lele dari Parung (Bogor), Losarang (Indramayu), dan Tulungagung.
Terbatas dan Fluktuatif
Menurut Aken Hafian, pembudidaya lele dari Desa Gunungsindur, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jabar, pasar lele memang masih terkonsentrasi di kota-kota besar untuk kebutuhan warung-warung tenda. Harga dipengaruhi oleh tiga hal, yakni cuaca, saprokan, dan kondisi sosial masyarakat. Inilah uniknya pasar lele. Tahun ajaran baru, jelang Idul Fitri, dan Idul Adha bisa membuat harga merosot. Pasalnya, pedagang pecel lele asal Jateng dan Jatim, terutama Lamongan, pulang kampung pada hari-hari besar tersebut. “Harga baru kembali normal sekitar sebulan kemudian,” ujar Aken.
Petani lele memang masih mengandalkan warung tenda sebagai pasar utamanya. Mereka mendapatkan bahan baku dari bandar atau agen. Inilah yang menjadi keprihatinan para pelaku usaha lele. Petani lele tidak mampu menentukan harga. Harga ditentukan oleh bandar. Bahkan, pelaku usaha lele sebesar Aken yang produksinya mencapai 200 ton per bulan pun tidak kuasa mengatur harga. Banjir lele yang biasanya terjadi saat musim penghujan jadi mimpi buruk petani. Mau dijual, harganya murah. Mau ditampung ujung-ujungnya rugi karena menguras pakan.
Di bawah bendera Jumbo Bintang Lestari (JBL), Aken pernah mencoba menyeragamkan harga di tingkat petani sekitar Parung, tapi gagal. “Hukum ekonomi yang berjalan. Tetap ada yang ingin mempertahankan pasar,” jelasnya. Sengitnya berebut laba dari lele bukan cuma berlaku antara petani dan bandar. Menurut Rahmad Akhadhan, petani dan pengurus koperasi lele “Argo Mino”, Boyolali, Jateng, bisnis lele kini sudah menjurus pada kanibalisme pasar.
Contohnya pasar lele lintas provinsi, dari Jatim ke Jateng atau dari Jateng ke Jabar dan DKI Jakarta. Padahal, menurut Rahmad, pasar Jateng tidak perlu disuplai dari Jatim karena produksinya cukup. Namun lele Jatim bisa masuk karena mereka berani memotong biaya transportasi. “Akhirnya petani sendiri yang jatuh-jatuhan harga,” ujar Rahmad.
Contoh lain adalah lele Boyolali yang sanggup menerobos pasar Jakarta. Padahal produksi lele di sekitar Jabodetabek dan Pantura tidak bisa dibilang kurang. “Kalau sudah begini, yang diuntungkan lagi-lagi ya bakul,” imbuh Rahmad.
Sejumlah petani mencoba keluar dari pasar tradisional ini dengan membuat produk berbahan baku lele. Salah satunya adalah H. Carmin, pembudidaya lele asal Losarang, Indramayu, yang memproduksi fillet lele. Juga kelompok petani lele “Mina Utama”, Boyolali, yang mengolah abon, nugget, dan kerupuk berbahan baku lele. Nilai tambah dari pengolahan lele tersebut cukup besar, sekitar 50% dari biaya produksi. Tantangan terbesar dalam usaha ini memang bukan pada teknologi pengolahannya, tapi pada pengenalan produk yang relatif belum dikenal masyarakat.
Enny Purbani T.