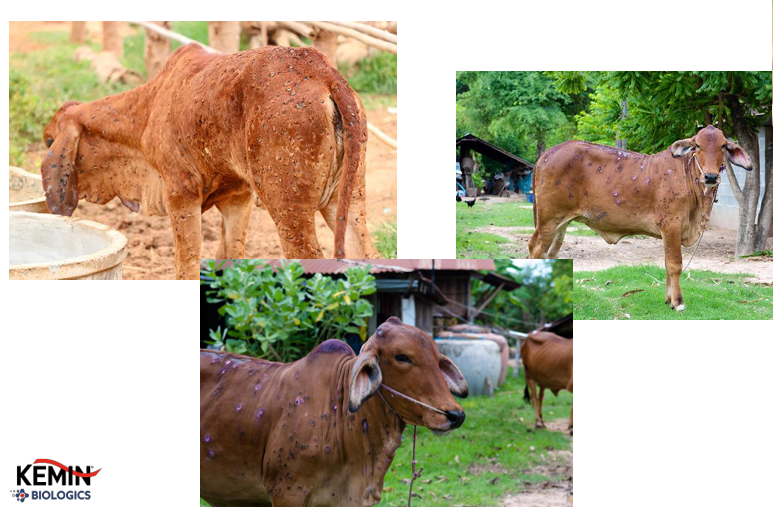Siklus budidaya cepat dan harga jual stabil membuat usaha ini bisa menjadi pilihan.
Kerimbunan pohon murbei menutupi halaman belakang rumahnya. Pagi hari, tumpukan dedaunan tanaman itu dibawanya ke sebuah bangunan yang di dalamnya dipadati rak-rak. Di atas rak bersusun tiga itu, ribuan ulat sutera melenggak-lenggok mengunyah daun murbei yang dipanennya dari kebun seluas 6 ha.
Tentu bukan tanpa alasan yang dilakukan Tatang Gazali tersebut. Selain mengisi masa pensiun, rutinitas itu kini menjadi mata pencahariannya. Menurut Tatang yang bermitra dengan sepuluhan orang, usaha ini berpeluang dikembangkan, mengingat kain sutera sebagai produk hilir tak pernah sepi peminat. Laba yang dijanjikan dari bisnis ini cukup mengiurkan. Dengan modal membeli dua boks ulat sutera kecil seharga Rp200 ribu, petani dapat menerima Rp2 juta per bulan.
Siklus Cepat
Ditemui AGRINA di kediamannya di kaki Gunung Salak, Ciapus, Bogor, Tatang menceritakan, setiap boks dapat menghasilkan 40 kg kokon per siklus (dua minggu). Harga kepompong atau biasa disebut kokon, menurutnya, saat ini terbilang stabil pada kisaran Rp25.000 per kg.
Satu boks berisi sekitar 25.000 telur ulat. Namun dalam proses penetasan, persentase keberhasilannya hanya sekitar 60%. Jadi, jumlah ulat yang dibesarkan hanya sekitar 16.000 ekor per boks. “Petani kalau bisa menghasilkan kepompong sekitar 40 kg dia sudah dapat Rp1 juta per boks,” ungkap pembudidaya yang sudah memulai usahanya sejak 2003 ini.
Petani yang tergabung dalam kemitraan bersama Tatang cuma diwajibkan membesarkan ulat kecil menjadi besar sampai menghasilkan kokon. Sedangkan penetasan dilakukan Tatang. Dirinya pula yang membeli kokon dari petani mitra. “Umpamanya menetaskan tanggal 1, terus umur 14 hari saya berikan ke petani sampai masa mengokon. Waktunya hanya 2 minggu. Jadi, habis bulan petani sudah dapat uang,” terang pensiunan PTPN di Bandung ini.
Kokon hasil pembesaran petani selanjutnya dipintal kakek berusia 73 tahun ini menjadi benang sutera. Langkahnya relatif panjang. Tahap awal kokon direbus selama 15 menit, diambil benangnya, kemudian digulung. Kemudian 3—4 lembar benang dirangkap menjadi satu dalam mesin twisting. Setelahnya hasil rangkapan dipilin, lalu masuk ke mesin rewinding untuk finishing.
Sekitar 70% benang sutera yang dihasilkan Tatang dijual ke penenun di kawasan Garut dan Lembang. Sisanya ditenun sendiri menjadi kain sutera. “Untuk pengunjung yang mau membeli cinderamata,“ alasan Tatang yang lokasi usahanya juga menjadi obyek agrowisata.
Telaten
Usaha pembesaran ulat sutera terbilang gampang–gampang susah. Pasalnya, kata Tatang, bisnis ini butuh ketelatenan. Jadwal makan yang mesti tepat dan kejelian mengamati perkembangan ulat menjadi tantangan tersendiri. “Kadang ada saat kita sedang mengantuk, ulat harus ditengok,” candanya.
Hitung-hitungan Tatang, idealnya petani ulat sutera mesti ditopang ketersediaan lahan minimal satu hektar. Luasan tersebut digunakan untuk mengembangkan tanaman murbei, pakan ulat sutera. Ulat ini termasuk peliharaan yang rakus. Terlihat dari jadwal makannya per hari yang mencapai 4 kali. Tak heran kebutuhan pakan satu boks ulat selama siklus pembesaran mencapai satu ton lebih. Dari luasan satu hektar dengan 20.000 batang pohon murbei dapat mencukupi kebutuhan dua boks ulat sutera.
Pakan bisanya diberikan setiap pukul tujuh pagi, sebelas siang, tiga sore, dan tujuh malam. Tatang malah mengaku memberi makan 5 kali sehari. Alasannya, “Supaya makannya banyak. Kalau makannya banyak, ‘kan jadi gemuk ulatnya. Pembentukan kepompong juga akan besar.”
Selamet Riyanto